
ANITA FITRIAWATI
140210302073
FKIP SEJARAH
UNIVERSITAS JEMBER

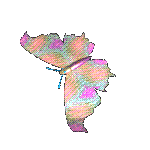


PENGANTAR ILMU SOSIAL
ILMU SEJARAH DAN ILMU SOSIAL
2.1. PENGERTIAN SEJARAH DAN ILMU SEJARAH
2.1.1. PENGERTIAN SEJARAH
Istilah sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata syajaratun (dibaca syajarah), yang memeiliki arti pohon kayu. Pengertian pohon kayu di sini adalah adanya suatu kejadian, perkembangan atau pertumbuhan tentang suatu hal (peristiwa) dalam suatu kesinambungan (konyinuitas). Selain itu, ada pula peneliti yang menganggap bahwa arti kata syajarah tidak sama dengan kata sejarah, sebab sejarah bukan hanya bermakna sebagai pohon keluarga, asal usul, atau silsilah. Walaupun demikian, diakui bahwa ada hubungan antara kata syajarah dengan kata sejarah, seseorang yang memepelajari sejarah berkaitan dengan cerita, silsilah, riwayat, dan asal usul tentang seseorang atau kejadian (Sjamsuddin, 1996:2). Dengan demikian, pengertian sejarah yang dipahami sekarang ini dari alih bahasa Inggris, yakni history yang bersumber dari bahasa Yunani kuno Historia (dibaca istoria) yang berarti belajar dengan cara bertanya-tanya. Kata historia diartikan sebagai telaahan mengenai gejala-gejala (terutama hal ihwal manusia) dalam urutan kronologis (Sjamsuddin dan Ismaun, 1996:4).
2.1.1.1. TUJUAN DAN KEGUNAAN SEJARAH
1. Fungsi Edukatif
Sejarah membewa dan mengajarkan kebijaksanaan ataupun kearifan-kearifan.
2. Fungsi Inspiratif
Dengan mempelajari sejarah dapat memberikan isnspirasi atau ilham.
3. Fungsi Instruktif
Denagn belajar sejarah dapat berperan dalam proses pembelajaran pada salah satu kejuruan atau ketrampilan tertentu, seperti navigasi, jurnalistik, dan sebagainya.
4. Fungsi Rekreasi
Belajar sejarah dapat memberikan rasa kesenangan maupun keindahan. Sebab dengan mempelajari berbagai peristiwa menarik di berbagai tempat, negara dan bangsa, kita ibarat berwisata ke berbagai negara di dunia.
2.1.2. PENGERTIAN ILMU SEJARAH
1. Menurut Aristoteles
Sejarah merupakan satu sistem yangmeneliti suatu kejadian sejak awal dan tersusun dalam bentuk kronologi. Pada masa yang sama menurut beliau juga Sejarah adalah peristiwa-peristiwa masa lalu yang mempunyai catatan dan bukti-bukti yang konkrit.
2. Menurut R.G.Collingwood
Sejarah ialah sebuah bentuk penyelidikan tentang hal-hal yang telah dilakukan manusia pada masa lampau.
3. Menurut M. Yamin
Sejarah merupakan ilmu pengetahuan dengan umumnya yang berhubungan dengan cerita bertarikh sebagai hasil penafsiran kejadian-kejadian dalam masyarakat manusia pada waktuyang telah lampau.
2.2. PENGERTIAN ILMU SOSIAL
Istilah ilmu sosial menurut Ralf Dahrendorf, seorang ahli sosiologi Jerman dan penulis buku Class and Class Confilct in Industrial Society yang dikenal sebagai pencetus Teori Konflik Non-Marxis, merupakan suatu konsep yang ambisius untuk mendefinisikan seperangkat disiplin akademik yang memberikan perhatian pada aspek-aspek kemasyarakatan manusia. Bentuk tunggal ilmu sosial menunjukan sebuah komunitas dan pendekatan yang saat ini hanya diklaim oleh beberapa orang saja; sedangkan bentuk jamaknya, ilmu-ilmu sosial, mungkin istilah tersebut merupakan bentuk yang lebih tepat. Ilmu-ilmu sosial mencakup sosiologi, antropologi, psikologi, ekonomi, geografi sosial, politik, bahkan sejarah walaupun di satu sisi ia termasuk ilmu humaniora (Dahrendorf, 2000:999).
Ilmu-ilmu sosial tumbuh dari filsafat moral, sebagaimana ilmu-ilmu alam tumbuh dari filsafat alam. Meskipun terdapat berbagai perbedaan pendapat tentang apa yang disebut ilmu-ilmu (ilmu sosial), namun semuanya mengarah kepada pemahaman yang sama bahwa ilmu sosial adalah ilmu yang memepelajari perilaku dan aktivitas sosial dalam kehidupan bersama.
2.3. SEBAB TERJADINYA HUBUNGAN ANTARA ILMU SEJARAH &
ILMU SOSIAL
Secara rinci Kartodirdjo (1992:120) mengemukakan sebab-sebabproses saling mendekatnya antara ilmu sejarah dan ilmu-ilmu sosial disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:
-
Sejarah deskriptif-naratif sudah tidak memuaskan lagi untuk menjelaskan berbagai masalah atau gejala yang serba kompleks. Karena obyek yang demikian memuat berbagai aspek atau dimensi permasalahan maka konsekuensi logis ialah pendekatan yang mampu mengungkapkannya;
-
Pendekatan ilmu sosial adalah yang paling tepat untuk dipergunakan sebagai cara menyelesaikan permasalahan;
-
Ilmu-ilmu sosial telah mengalami perkembangan pesat, sehingga dapat menyediakan teori dan konsep yang merupakan alat analitis yang relevan sekali untuk keperluan analisis historis;
-
Studi sejarah tidak terbatas pada pengkajian hal-hal informatif tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, tetapi juga ingin melacak berbagai struktur masyarakat, pola kelakuan, kecenderungan proses dalam berbagai bidang, dan lain-lain. Kesemuanya itu menuntut adanya alat analitis yang tajam dan mampu mengekstrapolasikan fakta, unsur, pola, dan sebagainya.
2.4. KEGUNAAN SEJARAH UNTUK ILMU-ILMU SOSIAL
2.4.1. SEJARAH SEBAGAI KRITIK TERHADAP ILMU-ILMU SOSIAL
Max Weber (1864-1920) dalam metodologi ilmu-ilmu sosial menggunakan tipe ideal untuk mempermudah penelitian, yang sangat berguna bagi sejarawan. Namun, ketika dihadapkan pada kenyataan historis yang faktual, ternyata tipe ideal itu banyak yang tidak memiliki dasar faktual. Buku Weber yang terkenal, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, menyatakan bahwa timbulnya kapitalisme ialah karena adanya semangat Protestanisme yang memperkenakan orang untuk menimbun kekayaan, tidak untuk dinikmati, tetepi untuk mengabdi kepada Tuhan. Jadi orang mulai menanam dan menanam modal. Buku Weber yang lain berjudul Religion of China, banyak dikecam karena mengandung kelemahan, Weber tidak peka dengan periodesasi sejarah. Dalam buku itu dia membuat kesimpulan-kesimpulan umum mengenai China dengan menghubungkan fakta-fakta dari periode yang berlainan.
2.4.2. PERMASALAHAN SEJARAH DAPAT MENJADI PERMASALAHAN ILMU-ILMU SOSIAL
Di Indonesia, banyak tulisan telah dibuat oleh para sosiolog dengan tema sosiologi pedesaan dengan permasalahan Tanam Paksa. Soedjito Sosrodihardjo menulis tentang struktur masyarakat Jawa, dan Loekman Soetrisno menulis tentang perubahan pedesaan, keduanya adalah sosiologi.
Contoh lain yang paling spektakuler ialah buku Barington Moore, Jr., Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World, yang membuat generalisasi tentang revolusi Inggris, Perancis, Amerika, Cina, Jepang, dan India. Barington Moore, Jr., membuat generalisasi tentang tiga jalan menuju dunia moderen. Jalan pertama ialah gabungan antara kapitalisme dan demokrasi parlementer, seperti ditempuh Revolusi Puritan, revolusi Perancis, dan Revolusi Amerika. Jalan kedua ialah juga kapitalisme, tetapi peran negara sangat dominan, sehinga ada revolusi dari atas yang bermuara pada fasisme, seperti dialami oleh Jerman dan Jepang. Jalan ketiga ialah lewat komunisme, seperti yang dialami oleh Rusia dan Cina.
2.4.3. PENDEKATANSEJARAH YANG BERSIFAT DIAKRONIS MENAMBAH DIMENSI BARU PADA ILMU-ILMU SOSIAL YANG SINKRONIS
Dua buku Clifford Geertz, Agricultural Involution: The Process of Ecological Change in Indonesia and The Social History of an Indonesian Town, adalah contoh penggunaan pendekatan sejarah untuk antropologi.
Buku Elly Touwen-Bouwsma, Staat, Islam en locale leiders in West Madura, Indonesia: Een historisch-anthropologisch studie (Negara, Islam dan penduduk lokal di Madura Timur, Indonesia: Sebuah studi sejarah-antropologi) selain merupakan hasil riset antropologi dengan penelitian lapangan, juga dikombinasikan dengan penemuan-penemuan sejarah.
2.5. KEGUNAAN ILMU-ILMU SOSIAL UNTUK SEJARAH
Pengaruh ilmu-ilmu sosial pada sejarah dapat digolongkan kepada empat macam, yaitu (1) konsep, (2) teori, (3) permasalahan, dan (4) pendekatan.
2.5.1. KONSEP
Kata konsep berasal dari bahasa Latin conceptus, yang berarti “ide”. Disadari atau tidak, sejarawan banyak menggunakan konsep ilmu-ilmu sosial. Contohnya adalah Anhar Gonggong dalam disertasinya tentang Kahar Muzakar menggunakan konsep local politics untuk menerangkan konflik antargolongan di Sulawesi Selatan. Untuk menjelaskan pribadi Kahar Muzakkar ia memakai konsep sirik dari ethno psychology yang berarti harga diri atau martabat. Demikianlah, Kahar harus pergi meranatau karena sirik dan kembali ke Sulawesi Selatan juga karena sirik.
2.5.2. TEORI
Kata teori berasal dari bahasa Yunani theoria, yang berarti “kaidah yang mendasari suatu gejala, yang sudah melalui verifikasi”. Contohnya adalah T. Ibrahim Alfian dalam bukunya Perang di Jalan Allah, menerangkan Perang Aceh dengan teori perilaku kolektif dari Neil J. Smelser. Dalam teori itu diterangkan bahwa perilaku kolektif timbul karena dua syarat, yaitu ketegangan struktural dan keyakinan yang tersebar. Adanya ketegangan antara rakyat Aceh dan pemerintah kolonial Belanda, antara muslim dan kafir, menghasilkan ideologi perang sabil di kalangan rakyat Aceh.
2.5.3. PERMASALAHAN
Dalam sejarah banyak sekali permasalahan ilmu-ilmu sosial yang dapat diangkat menjadi topik-topik penelitian sejarah. Soal seperti mobilitas sosial, kriminalitas, gerakan petani, migrasi, budaya istana, kebangkitan kelas menengah, dan sebagainya. Contohnya dalam buku karya Sartono Kartodirdjo yang berjudul Perkembangan Peradaban Priyayi. Buku itu ditulis berdasarkan permasalahan elit dalam pemerintahan kolonial Belanda, kemunculannya, lambang-lambangnya, dan perubahan-perubahannya.
2.5.4. PENDEKATAN
Sebenarnya, semua tulisan sejarah yang melibatkan penelitian suatu gejala sejarah dengan jangka yang relatif panjang dan melibatkan penelitian aspek ekonomi, masyarakat, atau politik, pastilah menggunakan juga pendekatan ilmu-ilmu sosial. Contohnya adalah disertasi Kuntowijoyo yang berjudul “Social Change in a Agrarian Society: Madura, 1850-1940”. Disertasi itu membicarakan Madura yang berubad dari patrimonialisme ke kolonialisme. Disertasi itu diantaranya, menanyakan mengapa dalam perubahan kelas tidak terjadi. Apa yang di sebut Vilfredo Pareto sebagai Circulation of the elites tidak ada di Madura. Ternyata jawabannya ialah karena Belanda menjamin bahwa para bangsawan akan dipekerjakan sebagai pegawai, baik sipil atau militer.
2.6. HUBUNGAN SEJARAH DENGAN ILMU-ILMU SOSIAL
2.6.1. HUBUNGAN SEJARAH DENGAN SOSIOLOGI
Hal ini lebih tampak lagi dengan cepatnya perubahan sosial jelas menarik perhatian bukan saja sejarawan, tetapi juga sosiologiwan. Sebab para sosiologiwan yang menganalisis berbagai persyaratan pembangunan pertanian dan industri di negara-negara yang disebut negara berkembang memperoleh kesan yang mereka kaji adalah tentang perubahan dari waktu ke waktu, dengan kata lain sejarah.
Sebagian di antaranya, seperti sosiologiwan Amerika Serikat Imanuel Wallerstein yang begitu tergoda untuk memperluas penyelidikannya hingga jauh ke masa silam, khususnya tentang Ekonomi Dunia Kapitalis (Wallerstein, 1996:537)
2.6.2. HUBUNAGN SEJARAH DENGAN ANTROPOLOGI
Hubungan ini dapat dilihat karena kedua disiplin ini memiliki persamaan yang menempatkan manusia sebagai subyek dan obyek kajiannya, lazimnya mencakup berbagai dimensi kehidupan. Dengan demikian, disamping melihat titik perbedaan, kedua disiplin itu pun memiliki persamaan. Bila sejarah membatasi diri pada penggambaran suatu peristiwa sebagai proses di masa lampau dalam bentuk cerita secara einmalig ‘sekali terjadi’, hal ini tidak termasuk bidang kajian antropologi. Namun, jika suatu penggambaran sejarah menampilkan suatu masyarakat di masa lampau dengan berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, politik, religi, dan keseniannya maka gambaran tersebut mencakup unsur-unsur kebudayaan masyarakat. Dalam hal itu ada persamaan bahkan tumpang-tindih antara sejarah dan antropologi (Kartodirdjo, 1992:153)
Memang ada persamaan yang menarik jika hal itu dihubungkan dengan ucapan antropolog terkemuka Evans-Pritchard. Ia mengemukakan bahwa Antropologi adalah Sejarah. Hal itu dapat dipahami karena dalam studi antropologi diperlukan pula penjelasan tentang struktur-struktur social yang berupa lembaga-lembaga, pranata, dan system-sistem, yang kesemuanya itu akan dapat diterangkan secara lebih jelas apabila diungkapkan bahwa struktur itu adalah produk dari suatu perkembangan masa lampau. Karena antropologi pun mempelajari obyek yang sama, yaitu tiga jenis fakta yang terdiri atas artifact, sociofact, dan mentifact, di mana semuanya adalah produk historis dan hanya dapat dijelaskan eksistensinya dengan melacak sejarah perkembangannya (Kartodirdjo, 1992:153).
2.6.3. HUBUNGAN ANTROPOLOGI BUDAYA DENGAN SEJARAH
Hal ini dapat dipahami,mengingat ada dua hal yang penting. Pertama, makna kebudayaan semakin meluas karena semakin luasnya perhatian para sejarawan, sosiologiwan, mengkritisi sastra, dan lain-lain. Perhatian semakin dicurahkan kepada kebudayaan popular, yakni sikap-sikap dan nilai-nilai masyarakat awam serta pengungkapannya ke dalam kesenian rakyat, lagu-lagu rakyat, cerita rakyat, festifal rakyat, dan lain-lain (Burke, 1978; Yeo dan Yeo, 1981). Kedua, mengingat semakin luasnya makna kebudayaan semakin meningkat pula kecenderungan untuk menganggap kebudayaan sebagai sesuatu yang aktif, bukan pasif. Kaun strukturalis tentu telah berusaha mengembalikan keseimbangan itu yang sudah terancam begitu lama, terutama Levi-Strauss, pada mulanya begitu membanggakan Karl Marx, akhirnya berpaling kembali kepada Hagel dengan mengatakan bahwa yang sebenar-benarnya struktur dalam bukanlah tatanan sosial dan ekonomi, melaikan kategori mental (Burke, 2001:178).
2.6.4. HUBUNGAN SEJARAH DENGAN PSIKOLOGI
Dalam cerita sejarah, aktor atau pelaku sejarah senantiasa mendapat sorotan yang tajam, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Sebagai actor individu, tidak lepas dari peranan faktor-faktor internal yang bersifat psikologis, seperti motivasi, minat, konsep diri, dan sebagainya yang selalu berinteraksi dengan faktor-faktor eksternal yang bersifat sosiologis, seperti lingkungan keluarga, lingkungan sosial budaya, dan sebagainya. Begitupun dalam aktor yang bersifat kelompok menunjukan aktivitas kolektif, yaitu suatu gejala yang menjadi obyek khusus psikologi sosial. Dalam berbagai peristiwa sejarah, perilaku kolektif sangat mencolok, anatara lain sewaktu ada huru hara,masa mengamuk (mob), gerakan sosial, atau protes yang revolusioner, semuanya menuntut penjelasn berdasarkan psikologis dari motivasi, sikap, dan tindakan kolektif (Kartodirdjo, 1992:139). Di situlah psikologi berperan untuk mengungkap beberapa faktor tersembunyi sebagai bagian proses mental.
2.6.5. HUBUNGAN SEJARAH DENGAN GEOGRAFI
Hubungan ini dapat dilihat dari suatu aksioma bahwa setiap peristiwa sejarah senantiasa memiliki lingkup temporal dan dan spasial (waktu dan ruang), dimana keduanya merupakan faktor yang membatasi fenomena sejarah tertentu sebagai unit (kesatuan), apakah itu perang,riwayat hidup, kerajaan, dan lain sebagainya (Kartodirdjo, 1992:130).
2.6.6. HUBUNGAN SEJARAH DENGAN ILMU EKONOMI
Walaupun kita tahu bahwa sejarah politik pada dua atau tiga abad terakhir begitu dominan dalam historiografi Barat, namun ironisnya mulai abad ke-20, sejarah ekonomi dalam berbagai aspeknya pun semakin menonjol, terutama setelah proses modernisasi, dimana hampir setiap bangsa di dunia lebih memfokuskan pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, proses industrialisasi beserta transformasi sosial yang mengikutinya menuntut pengkajian pertumbuhanekonomi dari sistem produksi agraris ke system produksi industrial (Kartodirdjo, 1992:136).
2.6.7. HUBUNGAN SEJARAH DENGAN ILMU POLITIK
Politik adalah sejarah masa kini, dan sejarah adalah politik masa lampau. Dalam hal ini, menunjukkan bahwa sejarah sering diidentikkan dengan politik, sejauh keduanya menunjukkan proses yang mencakup keterlibatan para aktor dalam interaksinya serta peranannya dalam usaha memperoleh “apa”, “kapan”, dan “bagaimana” (Kartodirdjo, 1992:148-149).
Di zaman sekarang, sebenarnya sejarah politik masih cukup menonjol, tetapi tidak sedominan masa lampau. Hal itu sangat menarik bahwa pengaruh ilmu politik dan ilmu-ilmu sosial sungguh besar dalam penulisan sejarah politik yang lebih tepat disebut sejarah politik gaya baru.
2.7. PERBEDAAN SEJARAH DENGAN ILMU SOSIAL
2.7.1. PERBEDAAN BERDASARKAN FAKTOR WAKTU & TEMPAT
Sejarah mempunyai kedudukan unik didalam rumpun ilmu-ilmu sosial. Meskipun sejarah termasuk sebagai salah satu dari ilmu-ilmu sosial, namun antara sejarah dan imu-ilmu sosial lainnya masih dapat dibedakan. Kajian sejarah terikat pada aspek temporal (waktu) terutama pada masa lampau (past). Faktor waktu ini menjadi pembeda antara sejarah dengan ilmu sosial lainnya, sehingga sering dikatakan bahwa sejarah adalah kajian yang berkaitan dengan manusia dan masyarakatnya pada masa lampau. Sedangkan ilmu-ilmu sosial mengkaji tentang manusia atau masyarakat manusia pada masa sekarang (present). Seringkali kajian dari ilmu-ilmu sosial itu digunakan untuk kepentingan masa yang akan datang atau untuk meramalkan (memprediksikan) kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada masa-masa yang akan datang (future).
Selain faktor waktu di kajian, sejarah juga terikat pada tempat (spasial) tertentu. Suatu peristiwa atau kejadian yang berhubungan dengan manusia atau masyarakat manusia pasti terjadi di suatu temapat tertentu. Kajian ilmu-ilmu sosial bukanlah tidak memperhatikan masa lampau tertentu, tetapi aspek kelampauan dan tempat khusus ini tidak terlalu dihiraukan.
2.7.2. PERBEDAAN BERDASARKAN PENDEKATAN ATAU PERSPEKTIF
Selanjutnya antara sejarah dan ilmu-ilmu sosial lainnya berbeda dalam pendekatan atau perspektif. Jika sejarah menggunakan pendekatan diakronik, maka ilmu-ilmu sosial menggunakan pendekatan sinkronik. Kajian sejarah meskipun tidak identik dengan kronik, tetapi kronologi (urutan waktu) dari kejadian-kejadian kedudukannya sangatlah penting. Fenomena sejarah yang hendak ditandai secara utuh memerlukan suatu pendekatan diakronik. Sebaliknya ilmu-ilmu sosial mencoba melihat fenomena peristiwa-peristiwa yang hampir sama pada tempat-tempat berbeda atau pada waktu yang berbeda-berbeda sehingga kelihatannya sebagai garis mendatar atau horizontal. Dengan saling ketergantungan fungsi unsur-unsur sehingga fenomena sebagai suatu kesatuan dapat ditandai dengan tepat.